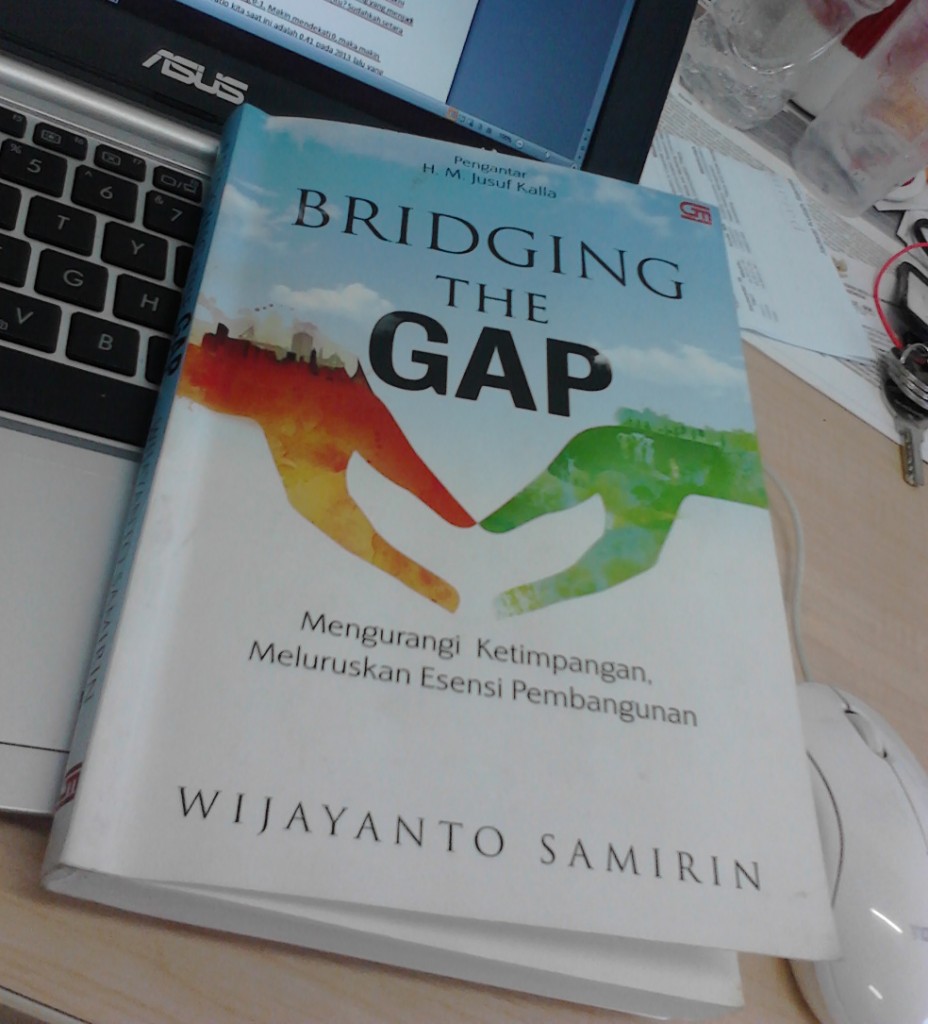- October 15, 2014
- Posted by: Septa Dinata
- Category: Books, Economy
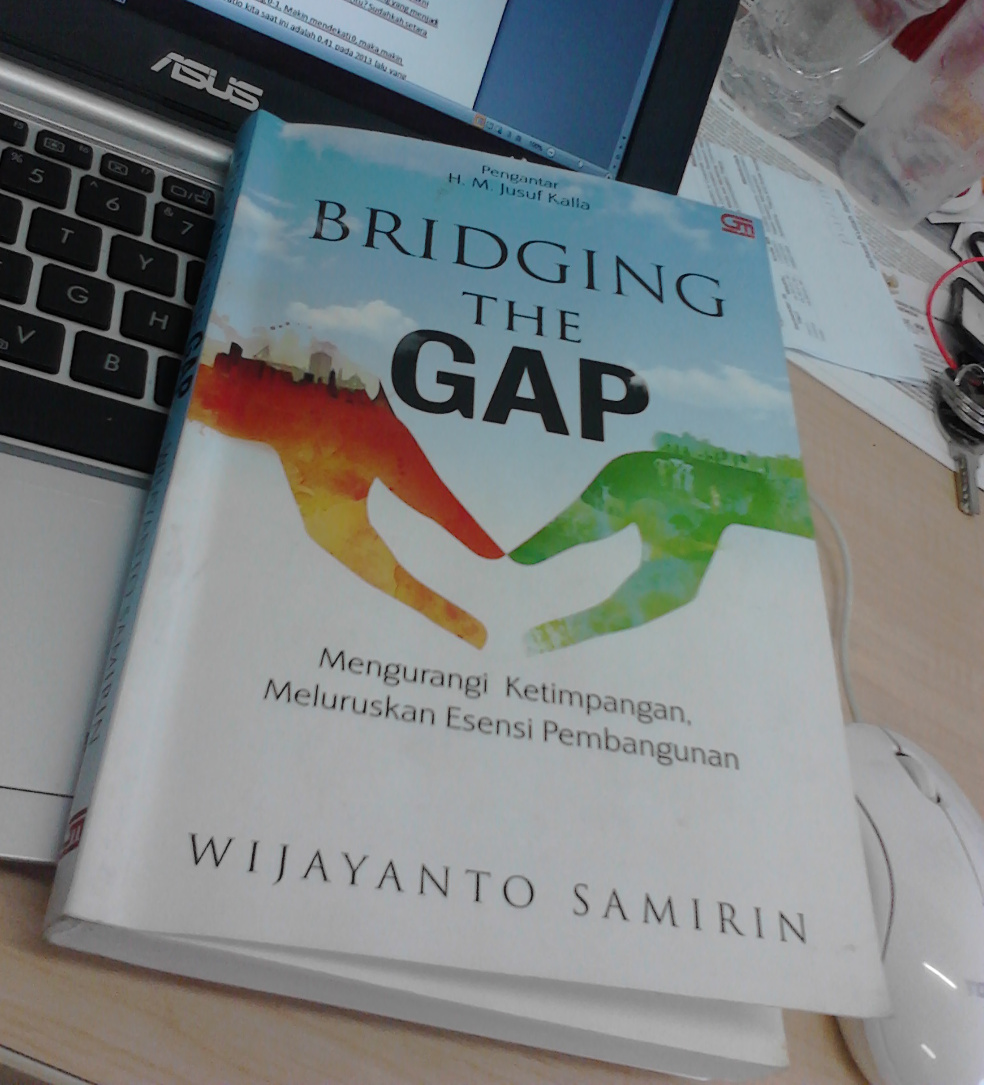
Dengan memandang apa yang dianggap kesuksesan oleh pemerintahan SBY yakni mempertahankan angka positif pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita bisa berbangga. Di tengah melesunya pertumbuhan ekonomi global, Indonesia masih bisa bertahan untuk tumbuh. Bukannya menggembirakan? Tentu.
Namun, bila dilihat ke dalam-dalam, ini seharusnya bisa lebih maksimal. Artinya, ‘Pemerintahan SBY tidak sukses-sukses amat,’ meminjam bahasa anak muda sekarang. Pada kuartal kedua 2011 pertumbuhan kita mencapai 6.5%. Tapi pada kuartal kedua 2014, pertumbuhan Indonesia terjungkal pada posisi 5.1%. Padahal tidak ada hujan tidak ada badai krisis, pertumbuhan kita marginnya malah menurun.
Lebih ke dalam lagi, dalam Bridging the Gap, terlepas dari menurunnya margin pertumbuhan, angka positif pertumbuhan ekonomi Indonesia sejatinya tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi tiap orang. Artinya, terjadi ketimpangan ekonomi di dalam tubuh bangsa ini. Sang penulis, WIjayanto Samirin, menggambarkan dengan apik balada ketimpangan ini.
Sang penulis ingin menunjukkan bahwa ukuran kemajuan ekonomi yakni pertumbuhan PDB tidaklah bisa menjadi patokan. Negara bisa maju dan tumbuh, tapi yang yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua elemen di dalamnya juga menikmati kemajuan itu? Sudahkah setara distribusi pertumbuhan itu?
Ukuran umum ketimpangan adalah gini ratio yang berentang 0-1. Makin mendekati 0, maka makin setara, dan makin timpang berlaku sebaliknya. Gini ratio kita saat ini adalah 0.41 pada 2013 lalu yang memburuk dari 0,34 pada 2003. WIjayanto menggambarkan kalau pada 1990, 10% kelompok terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan setara dengan 5,9 kali pendapata mereka di 10 persen kelompok termiskin. Namun pada tahun 2011, angka itu berubah drastis, naik menjadi 9,5 kali (hal. 28)
Ketimpangan ekonomi yang dibiarkan akan merembet pada dampak-dampak yang makin menyeret negara ini ke belakang. Beberapa di antaranya adalah naiknya tingkat kriminalitas, menurunnya kebahagiaan masyarakat, menurunnya kualitas kesehatan, hilangnya social trust, dan terakir potensi terganggunya stabilitas politik, keamanan sosial dan keberlanjutan kemajuan ekonomi.
Wijayanto pun mengajak pembaca bukunya untuk melihat best practice dari negara lain. Contoh yang paling ia tonjolkan adalah program Bolsa Familia di Brazil. Program ini ibarat peribasa, berilah kail, bukan ikannya. Untuk mengentaskan kemiskinan guna mengurangi ketimpangan, alih-alih memberikan bantuan dana langsung, pemerintah brazil memberi insentif pada mereka yang mau menyekolahkan anaknya dan mau ikut program kesehatan. Program ini sukses menurunkan angka anak kurang gizi sebesar 52 persen, penurunan kematian akibat diare 46 persen, tingka vaksinasi anak naik 100 persen dan banyak capaian lainnya (hal. 138)
Buku ini pun bukan tanpa solusi. Setidaknya ada 7 prioritas yang harus diambil pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan ketimpangan ini yakni (1) memasukkan kesetaraan sebagai target kinerja pembangunan, (2) menjaga tingkat inflasi dan suku bunga rendah, (3) meredefinisi kemiskinan dan pengangguran, (4) mengakhiri kebijakan yang mmperlebar ketimpangan, (5) memberikan perhatian khusu kepada para petani dan nelayan, (6) menerapkan kebijakan pajak progresif, dan (7) melakukan penguatan kapasitas bagi mereka yang miskin.
Buku ini tidak tebal, bisa habis dibaca semalam. Karena itu ada beberapa bagian yang akhirnya menimbulkan pertanyaan karena kurang elaborasi untuk membahas permasalahan ‘sebesar’ soal ketimpangan ini. Juga, banyak istilah ekonomi yang tidak mendapat penjelasan, sehingga kalau pembacanya belum pernah berkutat dalam dunia ini, ini akan sedikit membingungkan.
Tapi di luar itu, buku ini harus diakui bagus pengemasan bahasanya. Bagaimanapun juga, Wijayanto berhasil menyederhanakan masalah-masalah pelik dengan Bahasa yang popular. Ini juga akan sangat membantu bagi mereka yang ingin memahami dan ingin tahu, apa benar negara ini sudah dalam kondisi ‘tumbuh’ dan ‘sukses’ seperti kata SBY.
Akhirnya, pekerjaan untuk mengurangi ketimpangan tidak bisa dikerjakan sendiri. Menarik membaca quote yang ditulis sang penulis di bagian akhir buku ini, “If you want to go fast, please go alone; if you want to go far, let’s go together.” Mari bersama-sama memahami dan mencari solusi ketimpangan kita. (*)
Resensi oleh:
Rosyid Jazuli
Peneliti di PPPI
Judul: Bridging the Gap
Karya: Wijayanto Samirin
Tahun terbit: 2014
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Tebal: 197 halaman
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.