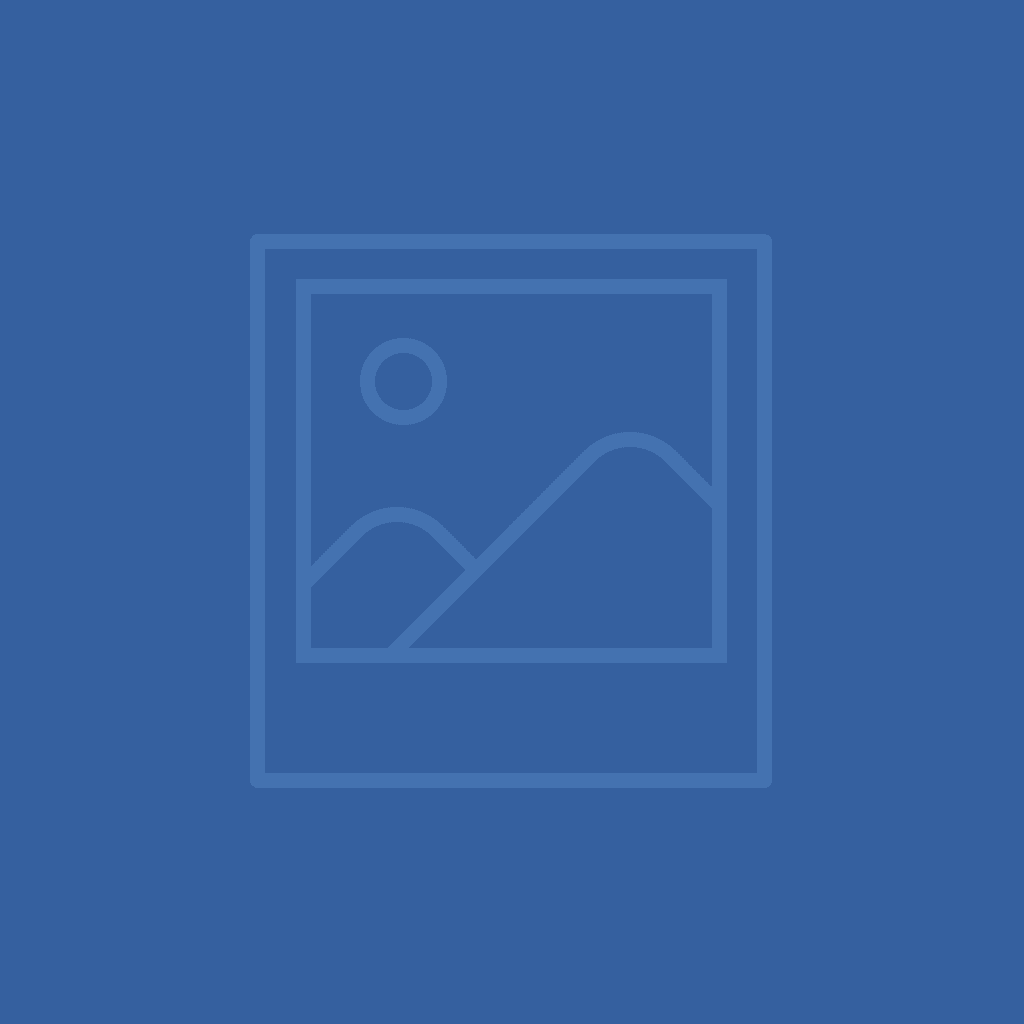BERITA PPPI, KOMPAS, 25/8/2025
Akal imitasi atau AI telah masuk ke ruang-ruang kelas. Kehadiran teknologi ini membantu proses pembelajaran sekaligus mengancam daya kritis generasi muda. Agar adopsi teknologi ini membawa manfaat, manusia juga perlu dilatih melalui literasi AI sedari sekolah.
Endri Aprianto, guru mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) madrasah aliyah negeri di Jakarta Timur; mengungkapkan tentang maraknya penggunaan AI di dalam kelas. ”Siswa itu mencari jawaban dari ChatGPT. Itu realita,” ucapnya di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Ia menyampaikan keluhan itu di sela-sela peluncuran Day of AI (DOAI) Indonesia di @america, Jakarta. DOAI Indonesia merupakan inisiatif nasional yang bertujuan memperkenalkan konsep AI kepada pelajar sekolah dasar dan menengah, termasuk terhadap para penyusun kurikulum dan bahan ajar AI.
Menurut Endri, dengan bantuan ChatGPT, siswa kini jauh lebih mudah menjawab berbagai soal dari guru. ”Jadi, guru juga mengeluh. Kita sudah capek-capek bikin soal, tiba-tiba anak-anak menyelesaikannya dalam 30 menit. Ternyata, mereka menggunakan ChatGPT,” ungkapnya.
Ia menilai, ketergantungan pada chatbot berbasis AI berpotensi melemahkan daya kritis siswa. Murid, lanjutnya, tidak lagi memahami konsep pembelajaran secara utuh karena merasa semua pertanyaan guru dapat diselesaikan oleh AI. Endri pun khawatir siswa terlalu bergantung pada AI.
Cerita Endri menjadi potret kecil pemanfaatan AI di dunia pendidikan. Survei internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025 menunjukkan, sebanyak 27,34 persen dari 8.700 responden menggunakan AI atau naik dari tahun sebelumnya 24,73 persen.
Generasi Z (kelahiran 1997-2012) dan milenial (1981-1996) menjadi kelompok pengguna AI terbesar dengan capaian masing-masing 43,7 persen dan 2,3 persen. Mereka paling sering mengakses konten edukasi dan pembelajaran, yakni 43,98 persen atau melonjak dari tahun sebelumnya, 21,84 persen.
Belum siap
Meskipun adopsi AI dalam dunia pendidikan meningkat, literasi AI justru belum memuaskan dengan skor 49,96. Hal ini menunjukkan tingkat literasi AI untuk responden masih kurang baik dan generasi Z dan milenial Indonesia belum cukup siap menghadapi perkembangan teknologi AI.
Literasi AI merupakan kemampuan dalam memahami bagaimana AI bekerja, mengenali risikonya, hingga mengadopsinya secara bertanggung jawab. Potret belum optimalnya literasi AI di dunia pendidikan tampak dari keluhan Endri, yaitu penggunaan AI untuk menyontek dan potensi penipuan.
Gambaran kondisi literasi AI Indonesia juga terlihat dari laporan perusahaan riset IPSOS bertajuk ”Global Views on AI 2023”. Penelitian itu menunjukkan, Indonesia adalah negara peringkat kedua dari 30 negara yang percaya bahwa AI tidak memiliki bias atau diskriminasi. Persentasenya, 76 persen.
Thailand menjadi negara pertama yang percaya (83 persen) AI tidak mengandung bias. Padahal, faktanya berbeda. Saat pengguna menulis instruksi (prompt) untuk menggambar dokter dan perawat, misalnya, AI menghasilkan dokter pria berkulit putih dan perempuan perawat berkulit berwarna.
”Ini menunjukkan AI bisa bias dalam menjawab,” kata Derry Wijaya, Koordinator Pelatihan Data Sains Monash University, Indonesia.
Begitu pula dengan keyakinan terhadap keamanan data saat perusahaan mengadopsi AI. Indonesia kembali di peringkat kedua yang meyakini data perusahaan tetap aman saat mengadopsi AI.
Padahal, menurut Derry, keamanan data menjadi krusial dalam penggunaan AI. Sebab, AI bisa disalahgunakan untuk mencuri data pribadi dan menipu korbannya.
”Artinya, kita (orang Indonesia) merasa tahu tentang AI. Tapi, sebenarnya kita tidak setahu itu,” ujarnya.
Derry mengingatkan, cara kerja AI generatif, seperti ChatGPT, mirip dengan fitur auto complete yang otomatis melengkapi kata saat sedang ditik ketika mengirim pesan di telepon pintar. Namun, AI terus dilatih dengan banyak data sehingga semakin pintar. Kemampuannya menjawab pertanyaan pun seolah-olah mendekati manusia.
Selain AI yang dilatih, manusia juga harus dilatih untuk menyesuaikan kemampuannya agar di masa depan kita tidak dikuasai AI.
”Selain AI yang dilatih, manusia juga harus dilatih untuk menyesuaikan kemampuannya agar di masa depan kita tidak dikuasai AI,” ujarnya.
Peningkatan pemahaman sumber daya manusia tentang AI menjadi penting, selain ketersediaan data, infrastruktur, dan sistem komputerisasi.
Pelatihan untuk pengguna juga dapat mencegah penyalahgunaan AI. Caranya, lanjutnya, melalui literasi AI di sekolah-sekolah. Beberapa hal yang perlu dipahami, AI sebaiknya digunakan untuk pembangunan ide. Saat melakukan riset dengan AI, siswa wajib memverifikasinya.
Saat menyusun kurikulum atau panduan pembelajaran AI, pihak sekolah atau pemerintah perlu bertanya ke murid dan guru terkait penggunaan AI serta tujuan besarnya. ”Kita harus bertanya ke murid dan guru karena mereka yang paling tahu kebutuhan pembelajarannya,” ungkapnya.
Garry Pawitandra Poluan, Advisory Day of AI Indonesia, sepakat, literasi AI sangat mendesak di tengah maraknya adopsi teknologi oleh masyarakat. Tanpa literasi mendalam di dunia pendidikan, siswa dan guru akan merasa takut memakai AI atau justru menyalahgunakan inovasi itu.
”Dulu, saya takut terbang. Saya lalu mencari layanan agar saya tidak takut naik pesawat. Ternyata, yang diajarkan kepada saya adalah bagaimana pesawat itu terbang, logika, dan cara kerjanya. Ini namanya literasi penerbangan. Begitu pula dengan literasi AI, yang mengajarkan cara kerja AI,” ujarnya.
Menurut Garry, literasi AI telah menjadi perhatian penduduk global. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan dan Kebudayaan (UNESCO), misalnya, memasukkan literasi AI dalam kerangka kerja kompetensi AI yang dapat menjadi panduan bagi guru dan siswa.
Pedoman khusus
Di Asia Tenggara, terdapat pedoman khusus penggunaan AI. Di Indonesia, ada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Regulasi itu, antara lain, mencantumkan mata pelajaran pilihan baru, yaitu Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA), sejak kelas 5 sekolah dasar. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, capaian pembelajarannya pun terkait algoritma pemrograman dan analisis data. Siswa pun dituntut memecahkan masalah dengan AI.
”Kalau kerangka kerja (Permendikdasmen) ini sebagai panduan yang harus diajarkan, Day of AI itu sebetulnya bentuk implementasinya karena di dalamnya ada kurikulumnya serta panduan yang bisa digunakan guru serta orangtua,” ungkap Garry. Program tersebut menyasar siswa usia 5-18 tahun.
Day of AI diinisiasi oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT), universitas riset ternama berbasis di Amerika Serikat, melalui program Responsible AI for Social Empowerment and Education (RAISE). Hingga kini, program itu menyentuh 170 negara, 30.000 guru, dan satu juta siswa.
Day of AI akan mengajarkan cara kerja AI, bagaimana pemanfaatan ChatGPT di sekolah, penggunaan AI untuk seni kreatif, hingga adopsinya di kehidupan sehari-hari. Pihaknya juga akan mengajak berbagai pihak menyusun kurikulum AI yang kontekstual dengan Indonesia hingga melatih para guru.
”Saat ini, ada beberapa guru yang membantu (menyusun kurikulum). Ini diperlukan karena kurikulumnya dibuat di Amerika. Butuh kontekstualisasi dan adaptasi dengan kondisi Indonesia,” ungkapnya. Saat ini, sebagian bahan ajar bisa diakses di https://dayofaiindonesia.org/.
Ismunandar, Head of Advisor Day of AI Indonesia, berharap, sekolah bisa mengadopsi berbagai panduan dalam mengajarkan AI. ”Dampak AI ini sangat besar pada pendidikan dan dunia kerja. Satu-satunya cara menghadapinya adalah menyiapkan diri kita dan anak-anaknya,” ujarnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, sesuai laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF), penguasaan terhadap AI dan mahadata merupakan keterampilan paling dibutuhkan dalam lima tahun ke depan. AI pun harus dikenalkan di jenjang pendidikan.
Kehadiran Day of AI Indonesia dan Permendikdasmen Nomor 13/2025 menandakan kesiapan bangsa mengadopsi AI. ”Kita harus semaksimal mungkin meminimalkan sisi negatif AI. Kita tidak hanya perlu menguasai teknologi, tetapi juga harus mengembangkan kesalehan digital,” ujarnya. (*)
Oleh Abdullah Fikri Ashri/KOMPAS
Artikel ini secara keseluruhan disadur dari publikasi KOMPAS. Garry Poluan yang dikutip dalam artikel tersebut juga merupakan Senior Fellow di PPPI.